Surat Etik, Kursi Senat, dan Matinya Nalar Akademik di Universitas Mataram
11 jam lalu
Universitas semestinya menjadi episentrum nalar dan kebebasan mimbar
Oleh : Muhammad Yoga Alhamid (Sekjend BEM Unram 2025)
Universitas semestinya menjadi episentrum nalar dan kebebasan mimbar. Universitas Mataram merupakan tempat integritas akademik dijunjung paling tinggi, jauh dari intrik politik praktis. Namun, apa jadinya jika koridor akademik justru disesaki manuver kekuasaan yang mengabaikan prosedur? Kasus yang menimpa Dr. Ansar di Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri (Fatepa) Universitas Mataram adalah kenyataan pahit dari realitas itu.
Sebuah "dosa" lama dari tahun 2018 perkara perlombaan LPPM yang sejatinya telah selesai pasca-gugatan PTUN dan pencabutan surat etik kala itu mendadak dibangkitkan kembali pada tahun 2025. Tiba-tiba, terbit Surat Keputusan Dekan No. 2362/UN18.F10/HK/2025 yang baru, yang memvonis Dr. Ansar dengan "pelanggaran etik berat".
Masalahnya, surat keputusan ini terbit ex nihilo yang lahir tanpa proses. Tak ada klarifikasi, tak ada pemanggilan tertulis, tak ada berita acara pemeriksaan (BAP), apalagi kesempatan bagi yang bersangkutan untuk membela diri. Ini bukan lagi soal penegakan etik, melainkan sebuah tindakan administratif yang cacat prosedural. Ketika sanksi dijatuhkan tanpa mekanisme check and balance, maka ini akan berubah dari instrumen penegak moral menjadi alat pemukul.
Mengapa surat ini terbit tepat di musim pemilihan anggota senat Universitas Mataram?
Jawabannya adalah politisasi. SK etik itu menjadi palu yang efektif untuk menjegal langkah Dr. Ansar. Dengan stempel "pelanggaran etik berat", jalannya menuju kursi senat universitas sebuah badan yang memiliki hak suara krusial dalam pemilihan rektor, otomatis terpotong. Tanpa kursi senat, satu suara yang dianggap "berseberangan" dengan pimpinan petahana berhasil diamputasi dari proses demokrasi kampus.
Ini adalah skenario pembunuhan karakter (character assassination) yang tampak terencana. Integritas, aset terpenting seorang akademisi, sengaja diserang untuk mendelegitimasi figur tersebut dari kontestasi politik di tingkat universitas.
Lebih ironis lagi, setelah Dr. Ansar kembali melakukan perlawanan hukum ke PTUN atas SK baru tersebut, pihak Dekanat akhirnya mencabut surat keputusan itu. Melalui surat No. 3155/UN18.F10/KP/2025 Pada Tanggal 30 September 2025. Pencabutan ini, secara de facto, adalah pengakuan tersirat akan kelemahan atau kesalahan fatal dalam penerbitan SK tersebut.
Namun, "nasi sudah menjadi bubur". Proses pemilihan anggota senat sudah telanjur lewat. Tujuan politik untuk menyingkirkan Dr. Ansar dari bursa senat telah tercapai, sekalipun instrumen yang digunakan terbukti keliru dan harus ditarik kembali. Hak politik sang dosen telah hilang, meski secara hukum ia "dimenangkan".
Secara teoretis, apa yang dialami Dr. Ansar dapat dianalisis dari pandangan Pierre Bourdieu mengenai "medan" (field) dan "kekerasan simbolik" (symbolic violence). Bourdieu memandang dunia akademik bukan hanya sebagai ruang nalar murni, tetapi sebagai sebuah "medan" pertarungan di mana para aktor bersaing untuk memperebutkan "modal simbolik" yakni prestise, kehormatan, dan integritas akademik.
Dalam konteks ini, SK etik yang cacat prosedur itu berfungsi sebagai instrumen "kekerasan simbolik". Sebuah tindakan pemaksaan makna oleh otoritas dominan (pimpinan) untuk secara sepihak mendefinisikan Dr. Ansar sebagai figur yang "cacat etik". Tujuannya jelas yaitu menghancurkan modal simbolik yang dimiliki Dr. Ansar, mendelegitimasinya di hadapan kolega, dan yang terpenting, menyingkirkannya dari arena kontestasi kekuasaan (pemilihan senat) tanpa perlu menggunakan paksaan fisik, melainkan cukup dengan memanipulasi aturan birokrasi yang paling sakral di kampus.
Kasus Dr. Ansar bukan sekadar sengketa personal antara seorang dosen dan pimpinannya. Kasus ini merupakan preseden berbahaya bagi iklim akademik. Ketika sanksi etik (instrumen paling sakral untuk menjaga muruah keilmuan) dapat diobral dan dijadikan komoditas politik demi kepentingan elektoral jangka pendek, independensi dan akal sehat kampus sedang dipertaruhkan.
Laporan ke Inspektorat Jenderal Kementerian Dikti kini menjadi pertaruhan terakhir. Ini bukan hanya soal desakan untuk mengulang pemilihan senat di FATEPA melainkan desakan untuk mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan wewenang dan mengembalikan marwah kampus sebagai benteng nalar, bukan arena politik transaksional yang menghalalkan segala cara.
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Kemudahan dalam Kecerdasan Buatan dan Ancaman yang Mengintai
Selasa, 16 September 2025 17:50 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0









 99
99 0
0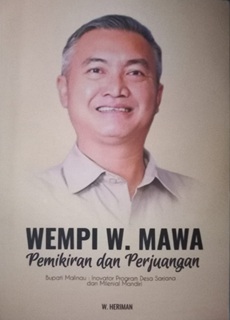




 Berita Pilihan
Berita Pilihan









